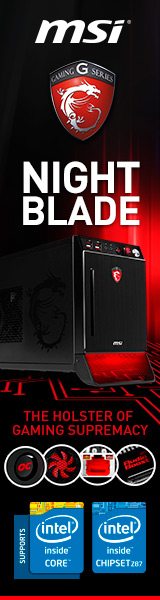Artikel
Oleh: Danny Putra Febriansyah, Fatia Nursa Atika
Pendidikan adalah salah satu alat untuk mempertahankan bahasa sebagai jati diri bangsa. Melalui pendidikan, generasi muda dapat ikut serta berperan menjaga martabat bahasa Indonesia agar tetap terjaga. Akan tetapi, kita kadang lupa apakah pendidikan ini mempunyai landasan yang kokoh guna menegakkan jati diri tersebut? Dalam kehidupan sehari-hari, akrab kita temui selipan jargon asing dan frasa campur aduk yang anehnya dianggap wajar, seolah-olah memang begitu resep menjadi bangsa yang besar. Apa yang sebenarnya terjadi dalam kehidupan sekarang? Apakah kamu merasa menggunakan bahasa Indonesia dan mencampur frasa dengan bahasa asing adalah suatu hal yang keren dan membanggakan? Apakah dengan demikian menunjukkan taring dan kredibilitas sebagai makhluk yang terpelajar sehingga mampu menguasai dunia? Ataukah sebenarnya orang-orang mulai melupakan kedaulatan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan? Bahkan, seorang sutradara dari sebuah film bertema kebangsaan dan merah putih yang baru-baru ini rilis sampai hati mengatakan bahwa “Bahasa Inggris bukanlah bahasa asing, tetapi bahasa sehari-hari yang sangat familiar.”
Bahasa Indonesia saat ini telah mencapai posisi berdaulat dan strategis di negeri sendiri. Bukan sekadar alat komunikasi, tetapi simbol identitas dan kedaulatan bangsa. Kedaulatan bahasa Indonesia memiliki arti bahwa bahasa ini diakui, digunakan, dan dihormati sebagai bahasa resmi negara, bahasa persatuan bangsa, serta bahasa pengantar utama dalam pendidikan, pemerintahan, dan komunikasi publik. Kedudukan bahasa Indonesia ini ditegaskan dalam Pasal 36 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa bahasa negara ialah bahasa Indonesia. Landasan hukum yang lebih terperinci termaktub dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan yang mengatur penggunaan bahasa Indonesia di berbagai bidang. Penguatan regulasi ini diperjelas melalui Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2019 tentang Penggunaan Bahasa Indonesia yang antara lain mengatur kewajiban penggunaan bahasa Indonesia dalam dokumen resmi negara, forum internasional yang melibatkan perwakilan Indonesia, dan penamaan bangunan, jalan, serta lembaga.
Kedaulatan bahasa Indonesia bukanlah hasil yang lahir dengan sendirinya tanpa perjuangan, melainkan buah dari perjalanan dan perjuangan panjang yang berdarah-darah. Dalam Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928, para pemuda dari berbagai daerah mengikrarkan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan sehingga menjadi alat pemersatu bangsa. Pilihan itu lahir di tengah keberagaman luar biasa dengan ratusan bahasa daerah. Para pendiri bangsa melihat bahasa Indonesia sebagai bahasa yang inklusif dan adil sehingga dapat diterima oleh semua kelompok etnis. Sekarang, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote, bahasa Indonesia digunakan dalam banyak situasi. Mulai dari rapat kenegaraan, kegiatan belajar-mengajar di sekolah atau kampus, siaran berita, hingga percakapan sehari-hari di ruang publik.
Akan tetapi, bahasa Indonesia harus menghadapi globalisasi, modernisasi, dan digitalisasi yang menjadi tembok tantangan di tengah kedaulatannya. Perkembangan teknologi komunikasi, media sosial, dan perdagangan daring membawa masuk kosakata asing secara masif ke ruang publik. Kata-kata bahasa asing seperti checkout, update, login, on the way, dan deadline lebih sering digunakan daripada padanan kata dalam bahasa Indonesia. Fenomena ini merupakan bagian dari proses akulturasi dan asimilasi bahasa yang alamiah terjadi di masyarakat. Jika tidak dikelola sekarang, keadaan ini akan menimbulkan pergeseran nilai dan persepsi, khususnya pada generasi muda. Bagi sebagian anak muda, bahasa asing dianggap lebih modern dan keren dibandingkan dengan bahasa Indonesia yang dipandang kaku dan kurang bergengsi. Tidak sedikit anak muda yang justru lebih mengenal latte dibanding ‘kopi susu’, menulis on the way (OTW) ketimbang ‘sedang dalam perjalanan’, menulis status dikejar deadline daripada dikejar ‘tenggat’, dan memilih judul film bertema kebangsaan dengan menyelipkan kosakata bahasa asing yang menyebabkan paradoks, alih-alih menggunakan judul film dengan keseluruhannya menggunakan bahasa Indonesia. Fenomena ini menjadi viral seketika di jagat maya. Film yang sasarannya adalah anak-anak dengan tujuan untuk mengedukasi justru tereduksi oleh kelalaian dalam penggunaan bahasa. Jika tren ini dilestarikan, bahasa Indonesia dapat berisiko kehilangan posisinya sebagai bahasa utama yang berdaulat.
Sejarah bahasa Indonesia memiliki daya tahan yang kuat. Hal ini terbukti dari bahasa Indonesia yang digunakan oleh lebih dari 275 juta penduduk dan diajarkan di lebih dari 50 negara. Hal ini juga menegaskan posisi bahasa Indonesia sebagai salah satu bahasa dengan penutur terbanyak di dunia. Keberadaan bahasa Indonesia juga berperan penting sebagai perekat nasional. Indonesia memiliki 718 bahasa daerah yang masing-masing menyimpan kekayaan budaya dan kearifan lokal. Dalam kehidupan sehari-hari, bahasa daerah tetap digunakan dalam lingkup kecil, tetapi untuk komunikasi antar-etnis dan antarwilayah, bahasa Indonesia menjadi jembatan yang menyatukan. Contohnya di pasar tradisional saat pedagang dari Bugis bertransaksi dengan pembeli dari Minangkabau, mereka menggunakan bahasa Indonesia agar memudahkan proses jual-beli.
Penguatan bahasa Indonesia tidak hanya bergantung pada masyarakat, tetapi juga pada keberadaan regulasi yang tegas. Selain UUD 1945, UU Nomor 24 Tahun 2009, dan Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2019, hadir pula Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Pengawasan Penggunaan Bahasa Indonesia. Regulasi terbaru ini menjadi tonggak krusial dalam memastikan bahasa Indonesia digunakan dengan baik dan benar di ruang publik dan dokumen negara. Selain itu, kedaulatan bahasa Indonesia sangat terkait dengan mutu Pendidikan. Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menegaskan bahwa pendidikan bertujuan untuk mengembangkan kemampuan, membentuk karakter anak bangsa, dan membangun peradaban bangsa yang bermartabat. Pendidikan juga bertujuan untuk membentuk peserta didik yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara demokratis yang bertanggung jawab. Seluruh visi ini membutuhkan media bahasa yang kuat dan seragam. Tenaga pengajar dan pendidik memerlukan bahasa baku untuk menyampaikan materi dengan jelas dan peserta didik membutuhkan bahasa yang tepat untuk memahami teks, soal ujian, dan diskusi ilmiah. Bahasa yang lemah akan menghambat pemahaman, sedangkan bahasa yang berdaulat akan memperlancar transfer ilmu pengetahuan.
Selain regulasi yang menjadi acuan dalam menjaga kedaulatan bahasa Indonesia, peran seorang duta bahasa yang dapat dijadikan representasi dan anutan juga sangat diperlukan. Duta menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti orang yang ditunjuk untuk mempromosikan sesuatu. Dalam konteks bahasa secara umumnya, duta bahasa mengambil peran salah satunya untuk mempromosikan atau menyampaikan informasi tentang program prioritas dari Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa serta menggaungkan slogan Trigatra Bangun Bahasa. Pemilihan Duta Bahasa dilakukan setiap tahun oleh Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa yang saat ini di bawah Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah melalui serangkaian seleksi di tingkat provinsi hinggat tingkat nasional.
Keberadaan duta bahasa menjadi simbol kolaborasi dan sinergi antara pemerintah dan generasi muda dalam menjaga jati diri bangsa melalui bahasa. Lebih dari sekadar titel belaka, duta bahasa adalah agen perubahan yang menginspirasi, bahwa cinta terhadap bahasa bukan hanya diwujudkan melalui kata-kata, tetapi juga melalui aksi nyata yang memberikan kebermanfaatan bagi masyarakat. Bentuk kontribusi nyata duta bahasa, yaitu dalam menjaga mutu pendidikan, khususnya dalam aspek literasi dan penguasaan bahasa. Dalam petualangan untuk menjalankan tugas dan mengimplementasikan krida kebahasaan dan kesastraan, duta bahasa sering berkolaborasi dengan sekolah, universitas, atau lembaga pendidikan nonformal guna menciptakan lingkungan belajar yang menghargai keberagaman bahasa dan budaya sambil tetap mengedepankan kualitas akademik.
Sebagai Duta Bahasa Provinsi Bengkulu, kami mengemban peran dan tanggung jawab yang begitu luar biasa yang nantinya akan meneruskan estafet perjuangan bangsa. Dengan visi yang seragam, yakni Indonesia Emas 2045, Danny dan Fatia (Daya) sebagai Duta Bahasa Provinsi Bengkulu Tahun 2025 menginisiasi sebuah krida kebahasaan dan kesastraan berjudul Sapa (Sahabat Bahasa Pelita Asa). Penciptaan krida kebahasaan dan kesastraan ini berdasarkan keresahan kami terhadap banyaknya sekolah dasar di Provinsi Bengkulu yang mendapatkan nilai Asesmen Nasional Literasi yang rendah. Sapa berangkat dari untaian benang asa yang kami rajut menjadi sesuatu yang berharga. Berbentuk sebuah kegiatan interaktif dan edukatif seputar literasi dan juga memuat pelestarian bahasa daerah dan pemanfaatan teknologi yang disusun sedemikian rupa menjadi sebuah buku panduan fasilitator Sapa. Karena rasa cinta terhadap bahasa inilah, Daya mengimplementasikan Sapa ke berbagai sekolah dasar di Kota Bengkulu sesuai dengan kriterianya. Saat itulah, kami melihat secercah benih harapan yang mulai tumbuh, semangat anak-anak untuk berpartisipasi, dan pahlawan tanpa tanda jasa yang juga ingin belajar dan berkontribusi menjadikan semuanya klop dalam satu visi dan misi. Dengan demikian, apabila terus berkelanjutan dan diimplementasikan di seluruh Indonesia, kami optimis suatu hari nanti, di masa depan, kita dapat menuai apa yang sudah kita tanam hari ini.
Pada dasarnya, bahasa Indonesia sudah menduduki singgasana berdaulat dan strategis di Indonesia. Kedaulatan yang didapat ini melalui proses yang begitu panjang dan melelahkan dan untuk mempertahankan kedaulatan tersebut juga tidaklah mudah. Banyak tantangan yang harus dihadapi. Marak terjadi tren di masyarakat yang menumbuhkan risiko terguncangnya kedaulatan bahasa Indonesia. Dalam hal ini, tentu yang bertanggung jawab bukanlah pemerintah saja, tetapi seluruh lapisan masyarakat, warga negara Indonesia, dari anak-anak hingga lansia memikul tanggung jawab yang sama dan harus bergerak untuk menunjukkan aksi yang nyata. Selain adanya regulasi yang menjadi pagar pengaman yang melindungi kedaulatan bahasa Indonesia dari ancaman, tentu ada sosok duta bahasa yang membantu untuk berkontribusi secara nyata dan memberikan kebermanfaatan bagi masyarakat melalui krida kebahasaan dan kesastraan. Dengan demikian, apabila seluruh lapisan masyarakat dapat bekerja sama dan menyelaraskan visi serta misi, benih baik yang kita tanam di tanah subur kita hari ini akan dapat kita tuai di kemudian hari. Pada seratus tahun kemerdekaan Indonesia nanti, para generasi muda hari ini akan ada yang menjadi pemimpin, sosok yang berpengaruh, akademisi, dan peran lainnya di masyarakat yang perlu dipersiapkan sedari dini. Kami percaya, akan meneruskan estafet perjuangan para pahlawan terdahulu. Kami tidak berperang menggunakan bambu runcing, tetapi kami berperang dengan meruncingkan literasi dan kebahasaan.